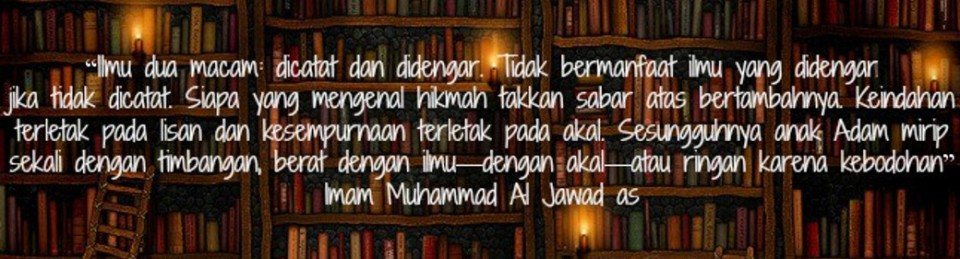Tag
Ayatullah Murtadha Muthahhari, Chris Barker, Claude Guillot, Denys Lombard, E.B. Taylor, Henri Chambert-Loir, Raymond Williams
oleh Sulaiman Djaya (Radar Banten, 15 April 2016)
Untuk melihat sebuah masyarakat, geliat dan kemajuannya, kita dapat mengkajinya dari sudut sejarah atau kebudayaan, yang dengan sendirinya dengan dua sudut pandang itu akan tersertakan dan terkaji juga aspek sosial, budaya, kreativitas saintifik, kemajuan ilmu pengetahuan dan politiknya.
Terkait dengan sejarah, pandangan Ayatullah Murtadha Muthahhari, tentang apa dan bagaimana sejarah itu harus dipahami dan dijadikan sebagai perspektif dan khazanah untuk membaca dan menganalisa masyarakat atau bangsa, cukup menarik dan jenius, karena Muthahhari memandang sejarah dengan memasukkan geliat budaya, sosial, faktor ilmu pengetahuan, kemajuan saintifik dan politik sebuah masyarakat atau bangsa.
Ayatullah Murtadha Muthahhari pun menegaskan bahwa ‘sejarah’ hanya berlaku bagi manusia, bukan binatang, karena hanya manusia-lah yang sanggup membangun peradaban, mengembangkan bahasa, sains dan ilmu pengetahuan mereka. Sementara binatang hanya bertahan hidup berdasarkan insting belaka, yang karena itulah manusia, dalam bahasa Arab, disebut juga ‘Al-hayawan an naathiq’ (binatang yang sanggup berpikir dan berbahasa).
Pandangan dan filsafat sejarah dan kebudayaan Ayatullah Murtadha Muthahhari itu cukup relevan dan menarik untuk ‘melihat’, mengkaji, dan ‘membaca’ kesejarahan dan aspek-aspek kultural, sosial dan politik Banten saat ini, sembari kita ‘mengkomparasinya’ dengan ‘realitas’ perjalanan kesejarahan Banten di masa silam: apakah Banten, secara kesejarahan, mengalami kemajuan atau sebaliknya? Apakah Banten secara kultural dan politik telah mengalami pencerahan atau belum beranjak dari kejumudan menuju progress yang diharapkan? Apakah secara sosial dan politik, Banten telah dapat dikatakan sebagai masyarakat yang maju atau belum?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus diajukan jika kita ingin mengkaji dan membaca Banten saat ini dan ke depan, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan dalam rangka menemukan visi saat ini dan ke depan.
Dalam perspektif filsafat sejarah Ayatullah Murtadha Muthahhari itu, sebagai contohnya, bangsa atau masyarakat yang akan survive dan maju adalah bangsa yang memiliki visi dan ideologi yang menjadi landasan kokoh politik dan kulturalnya dan orientasi bagi tindakan dan kebijakan-kebijakannya.
Pertanyaannya adalah: apakah Banten, lebih tepatnya para pemimpin di Banten, memiliki ‘visi’ dan tak hanya melakukan rutinitas pragmatisme politik dan birokratis setelah mereka memenangkan suksesi? Pertanyaan itu sangat penting untuk konteks saat ini dan ke depan, jika Banten ingin berkembang, maju dan mengalami progress secara kultural, intelektual, saintifik, ekonomi, dan politik, sebagaimana yang di-idealkan filsafat sejarahnya Ayatullah Murtadha Muthahhari tentang bangsa atau masyarakat yang akan mampu ‘menjadi pencipta’ sejarah dan pembangun peradaban.
Dalam rangka melihat kembali Banten dengan perspektif filsafat sejarah dan perspektif kebudayaan ini, penting juga membaca Banten dari sudut historis-antropologis (yang tentu saja sebagai analisa dan perspektif penguat ketika kita melihat dan membaca Banten dari perspektif filsafat sejarah dan sudut pandang kebudayaan) itu.
Terkait dengan itu, perlu juga ditegaskan bahwa kebudayaan bukanlah semata entitas dan unsur sampingan, tapi merupakan “pembentuk” siapa dan “apa” masyarakat itu sendiri. Hingga dapatlah dikatakan, masyarakat dan bangsa yang tidak memiliki sastra, seni, dan budaya adalah masyarakat dan bangsa yang tak memiliki jiwa.
Bersamaan dengan itu, ada banyak definisi dan pengertian kebudayaan, yang dengan beberapa definisi dan pengertian tersebut, setidak-tidaknya kita akan dapat mengidentifikasi segala produk dan jenis kebudayaan itu sendiri. Contoh definisi dan pengertian kebudayaan itu, misalnya, mengatakan kebudayaan merupakan suatu “proses” perkembangan yang sifatnya intelektual, estetis, dan bahkan spiritual.
Sementara itu, secara etnografis dan antropologis, kebudayaan dapat dipahami sebagai pandangan hidup dari suatu masyarakat tertentu. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa kebudayaan adalah juga karya dan praktik-praktik intelektual yang sifatnya literer dan artistik.
Meskipun demikian, kebudayaan itu sendiri bila kita memahaminya sebagai sebuah proses dan kreativitas, bisa menjadi berkembang, bertahan, atau hilang ketika berhadapan dengan situasi baru atau perkembangan jaman, di mana kemajuan tekhnologi dan percepatan ekonomi kapitalisme saat ini, sebagai contohnya, telah menggantikan dan menggusur praktik-praktik dan bahkan norma-norma yang pernah dianut dan dipercayai oleh masyarakat. Jika demikian, maka apa yang akan kita sebut kebudayaan sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan sebagai medan atau arena pertarungan kreativitas dan perkembangan intelektual itu sendiri.
Seperti telah sama-sama kita tahu, banyak sekali bentuk-bentuk dan jenis-jenis kebudayaan masyarakat yang pernah ada, saat ini telah hilang, atau tak lagi dipercayai dan dipraktikkan oleh masyarakat yang pernah mempercayainya, mempraktikkannya, dan memproduksinya karena faktor pergesekan dan pertarungan dengan perkembangan politis, ekonomis, dan sosiologis masyarakat sekarang yang harus diakui mengalami gempuran setiap hari, yang seakan tanpa jeda, dari hiruk-pikuk apa yang lazim disebut sebagai jaman kapitalisme mutakhir saat ini.
Akan tetapi, beberapa waktu belakangan ini, yang oleh beberapa pemikir dan pemerhati kebudayaan mengganggapnya merupakan bentuk encounter dan arah-balik pencaharian dahaga spiritual akibat kejenuhan, untuk tidak mengatakan sebagai kekeringan spiritual, masyarakat modern, yang bersama-sama gerakan ekologis, berusaha menggali dan menghidupkan kembali kearifan-kearifan lokal, yang sebagiannya masih ada di saat kebanyakannya sebenarnya telah menghilang alias tak lagi dipercaya, dipraktikkan atau pun diproduksi. Tak terkecuali untuk kasus Banten, yang secara historis merupakan tempat hidupnya sejumlah kebudayaan kuno yang pernah ada.
Sebagai kompleks wawasan, praktik, dan produk intelektual, E.B. Taylor, misalnya, mendefinisikan kebudayaan sebagai kesuluruhan pengetahuan, seni, hukum, adat-istiadat, norma keyakinan, dan juga kebiasaan atau custom yang hidup, ada, dianut, dan dipraktikan oleh suatu masyarakat atau komunitas kebudayaan.
Tidak jauh berbeda dengan artian kebudayaan yang dikemukakan E.B. Taylor tersebut, para pemikir dan penulis Cultural Studies, semisal Raymond Williams dan Chris Barker, untuk menyebut dua contoh lainnya, memandang dan memahami kebudayaan sebagai sesuatu atau hal-hal yang dihidupi, sejenis living culture, dalam kehidupan sehari-hari alias keseharian masyarakat itu sendiri.
Meskipun Raymond Williams dan Chris Barker dikenal sebagai pemikir dan penulis Cultural Studies, namun definisi kebudayaan yang mereka ajukan tersebut masih tergolong arti kebudayaan dalam ranah dan pengertian antropologis seperti yang dikemukakan E.B. Taylor. Di mana kebudayaan merupakan kompleks wawasan dan praktik yang di dalamnya juga mencakup produk-produk benda atau materi, norma, dan simbol-simbol yang ada dan dihidupi oleh sebuah atau suatu masyarakat.
Selain definisi dan identifikasi kebudayaan seperti yang telah dikemukakan E.B. Taylor, Raymond Williams, dan Chris Barker yang berwawasan sosiologis dan antropologis itu, hal lain yang juga penting untuk mengidentifikasi kebudayaan Banten adalah sejarah, dan juga arkeologi budaya, Banten itu sendiri.
Dari sudut pandang dan pendekatan historis yang sifatnya kronik ini, contohnya, kita dapat melacak lahir, tumbuh, dan keberadaan kebudayaan Banten dalam perjalanan sejarah masyarakat Banten, seperti kebudayaan yang berkaitan dengan aspek sejarah keagamaan yang di dalamnya mencakup ritual, peninggalan benda-benda keagamaan dan arsitektur, sebagai contohnya, dari mulai pra-sejarah Banten, era Hindu-Budha, hingga datangnya Islam.
Jika kebudayaan memang sekompleks wawasan dan kepercayaan yang koheren seperti yang dikemukakan E.B. Taylor itu, maka dapatlah dikatakan beberapa kesenian masyarakat Banten lahir dan berkembang bersama-sama dengan wawasan religius dan atau praktik-praktik dan kepercayaan keagamaan yang dianut masyarakat Banten, dari semenjak era pra-Islam hingga ketika Banten menganut agama Islam.
Rupa-rupanya, bila kita mencermati kebudayaan dari segi tilikan historis dan yang sifatnya kronik ini, kebudayaan Banten sedikit-banyaknya memang lahir, berkembang, dipraktikkan, dan “didasarkan” pada wawasan keagamaan, selain karena memang lahir dan bersumber dari kearifan-kearifan lokal-asli masyarakat Banten.
Di sinilah, jika kebudayaan juga dipahami sebagai kreativitas, kebudayaan masyarakat Banten dapat dikatakan sebagai bertemu dan berpadunya “kebudayaan lokal” masyarakat Banten itu sendiri dengan pengaruh-pengaruh wawasan keagamaan yang kemudian datang dan memperkaya alias melengkapinya, jika tidak dibilang turut juga merubah bentuk dan makna kebudayaan masyarakat Banten itu sendiri.
Secara historis pula, Banten bahkan bisa dikatakan sebagai “Negeri Terminal Sejarah Interaksi” sejumlah jenis, bentuk atau ragam kebudayaan dan keagamaan, bila kita meminjam istilahnya Denys Lombard dan Henri Chambert-Loir. Di mana dalam sejarahnya yang panjang, Banten memang telah menjadi semacam “jalur persinggahan” alias Carrefour beragam pengaruh keagamaan dan kebudayaan dalam skala sejarah Nusantara, ketika pengaruh kebudayaan India, Cina, dan kemudian Islam kemudian hadir dan bertemu, entah kemudian saling-melengkapi atau mengalami “kontestasi”.
Dalam hal ini, bukti yang paling nyata adalah sejumlah peninggalan benda dan arsitektur Kesultanan Banten, yang mencerminkan bentuk dan ekspressi simbolik yang sifatnya multikultur alias “ragam jejak kebudayaan”, semisal era pra-Islam, Cina, dan Eropa.
Tak hanya dalam arsitektur dan benda-benda, sejumlah kesenian tradisional dan kesenian keagamaan masyarakat Banten juga menunjukkan jejak-pengaruh ragam-budaya tersebut, entah kemudian saling-melengkapi atau mengalami “kontestasi”, yang pastilah mencerminkan kreativitas kebudayaan masyarakat Banten itu sendiri.
Secara historis, sebagaimana yang dikemukakan banyak sejarawan dan arkeolog, Banten adalah “negeri” dan “masyarakat” yang tua, yang memiliki sejarah yang panjang, yang pastilah juga menyangkut kebudayaannya, bila kebudayaan lahir, ada, dan berkembangnya sebuah kebudayaan juga dipahami sebagai “interaksi historis-kultural” seperti yang dikatakan Denys Lombard dan Henri Chambert-Loir itu.
Di Banten, sebagaimana dikemukakan para sejarawan dan arkeolog, “yang Sunda”, “yang Jawa”, dan “yang Melayu” bertemu dan berpadu, yang kemudian membentuk sejarah, identitas, dan budaya Banten itu sendiri. Hingga apa yang kita sebut Banten, demikian ujar Claude Guillot, adalah ketiganya sekaligus. Meskipun tentu saja, secara historis pula, tentulah masih dapat dilacak dan dikaji unsur-unsur lokal Banten sebelum Islam menjadi wawasan dan lanskap dominan kepercayaan dan juga “wawasan kebudayaan” masyarakat Banten, yang dalam sejarahnya memang telah mengalami pembauran alias akulturasi yang saling melengkapi dan memperkaya antara warisan “lokal pra-Islam” dengan unsur-unsur Islam, semisal dalam seni tradisi, adat, kesusastraan, arsitektur, dan yang lainnya yang banyak jumlahnya.
Seperti telah kita lihat dengan contoh-contoh yang disebutkan itu, ada suatu masa dan jaman ketika Banten membangun ‘sejarah’ dan menjadi pemain dominan dalam sejarah secara politik dan ekonomi, dan pada saat bersamaan memiliki dan mengembangkan produk-produk kebudayaan dan intelektualnya, seni dan kearifannya. Pertanyaannya adalah: ‘Bagaimana dengan Banten saat ini dan kedepan?”